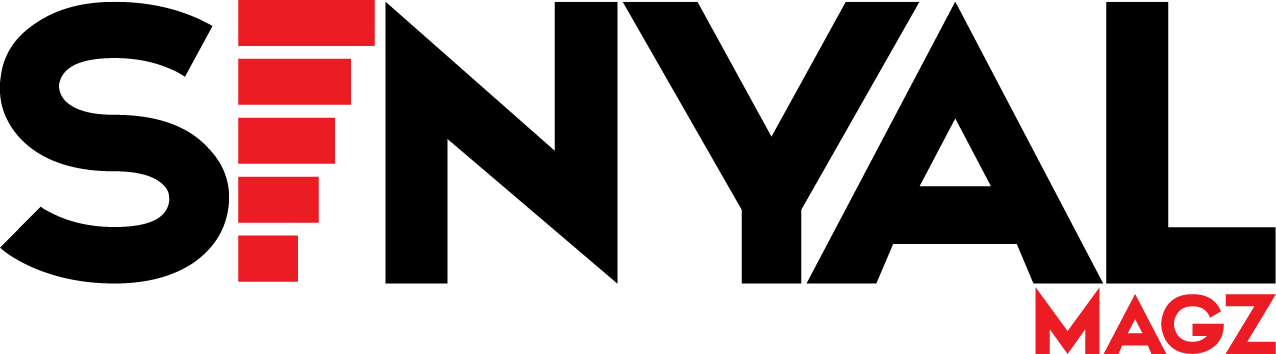FILM dokumenter pra sampai pasca perang dunia pertama (PD1) di televisi kabel minggu ini menampilkan dengan gamblang apa yang terjadi, saat bersamaan dengan merebaknya wabah “Flu Spanyol” dari Januari 1918 sampai Desember 1920. Flu itu, seperti diungkap oleh Presiden keenam Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono, memakan korban sampai 50 juta jiwa di seluruh dunia, sementara film tadi menyebut antara 50 juta sampai 100 juta jiwa.
Jumlah korban tinggi karena Pemerintah Presiden AS Woodrow Wilson (1856-1924) pada tahun 1917 sangat abai pada pandemi flu spanyol tadi, akibat lebih fokus pada perang dunia pertama tahun 1914 hingga 1918. Flu itu merebak, bukan dari spanyol, konon malah dari Philadelphia, AS, pada Januari 1917 persis saat AS terpancing terjun ke PD1 gara-gara tiga kapalnya ditorpedo kapal selam Jerman.
Pemerintahan Wilson sibuk merekrut lebih dari 1,2 juta tentara untuk dikerahkan ke medan perang, membangun industri pertahanan hingga anggaran federal melejit dari 1 miliar dollar AS pada 1916 menjadi 19 miliar dollar AS pada 1919. Tentara Amerika, mayoritas remaja dan pemuda yang termakan propaganda masif pemerintah soal bela negara, banyak yang sudah membawa bibit flu spanyol ke medan perang di Eropa. Sementara Spanyol sendiri tidak ikut perang.
Jutaan tentara di Amerika dan di Eropa, puluhan juta anggota keluarga dan lingkungannya terpapar flu, dan jumlah penderita sampai 500 juta, hanya dalam waktu 2 tahun. Presiden, bahkan juga menteri kesehatannya tidak sadar bahaya flu spanyol, baru mulai sadar ketika level elit juga kena, bahkan Presiden Woodrow Wilson pun kena.
Wilson pun sakit pada tahun 1918, sembuh setahun kemudian dan – seperti tanda-tanda hampir semua korban yang kemudian sembuh – kemampuannya jadi tampak berkurang. Ia menderita stroke pada tahun 1919 dan lumpuh hingga akhir masa tugasnya sebagai presiden pada 1921, wafat tahun 1924 dalam usia 67 tahun.
Mungkin waktu itu Spanyol belum seperti Tiongkok sekarang, ketika flu disebut sebagai flu spanyol, beda dengan sekarang ketika virus corona (Covid-19) disebut oleh Presiden Trump sebagai Virus China. Masyarakat protes, tetapi Spanyol diam-diam saja, walau flu itu juga sempat merebak di Spanyol.
Rezekinya amblas
Kisah Italia juga mirip dengan kita, menganggap enteng virus corona. Kalau di Italia, juga di AS sekarang, orang masih berkeliaran di jalan, pesta-pesta masih berlangsung, kita juga sama. Angkutan umum masih padat penumpang, pasar kaki lima masih dipenuhi masyarakat, pesta kawin masih berlangsung, dan sebagian orang protes pada imbauan peniadaan shalat berjamaah. Bahkan puluhan ribu orang curi start pulang mudik.
Jumlah kasus di Italia pun jadi jauh lebih banyak dibanding China. Data Universitas John Hopkins (AS) Jumat (27/3) menyebutkan kasus terbanyak adalah Amerika yang justru “didatangi belakangan” oleh virus, sebesar 85.505 kasus. China mencapai 81.782 kasus, Italia 80.589 kasus dengan kematian tertinggi sebanyak 8.215 dan China 3.169.
Indonesia, yang virusnya pernah dilecehkan salah seorang petinggi kita, memang “baru” 1.046 kasus dari 267 juta penduduk dengan kematian mencapai 87 orang (8,31 persen). Persentase kematian di Indonesia jauh lebih tingi dibanding rata-rata dunia yang 4,51 persen.
China dalam waktu tujuh minggu berhasil membersihkan negaranya dari Covid-19 karena segera melaksanakan sterilisasi, menutup kota-kota (locked down) dimulai dari Wuhan. Indonesia mengalahkan Italia dalam kelambatan melakukan lockdown karena Indonesia masih sibuk membahas perlu tidaknya locked down, bahkan Tegal ditegur karena sudah memulainya sementara Itali sudah mendahului.
Banyak masalah yang harus dipertimbangkan. Dengan imbauan jaga jarak (social distancing) dan penutupan berbagai fasilitas umum saja, masyarakat cuek karena memang imbauan tidak disertai solusi.
Ratusan ribu mitra OJOL (ojek online), warung tegal (warteg) dan sejenisnya, pedagang asongan, pekerja harian, tiba-tiba saja rezekinya amblas, orang mulai tidak mau bepergian, takut membeli makanan yang dijual terbuka. Bukannya tidak mau, tetapi justru masyarakat kalangan bawah yang tempat tinggalnya tanpa distancing di kampung-kampung Jakarta, tidak bisa membeli masker.
Harga masker melambung karena ulah spekulan yang menjual 50 lembar seharga Rp 400.000, sementara pemerintah tidak memberi solusi dengan misalnya bertindak keras, hanya mampu mengancam. Dokter, perawat, petugas rumah sakit, bertumbangan syahid karena alat pelindung diri (APD) tidak tersedia, dan konyolnya APD sumbangan China justru buatan Indonesia.
Orang kecil lebih kebal?
Pemerintah memang sibuk turun tangan dengan melakukan sosialisasi soal bahayanya Covid-19 dan operator telekomunikasi turun tangan dengan memberi kemudahan lewat penyediaan pita selebar 30 GB. Sayangnya itu tidak sampai ke kalangan bawah yang hidup berimpitan tadi. Tidak semua punya ponsel pintar.
Agak tidak masuk akal, korban-korban virus korona bukan orang sembarangan, setidaknya kelas menengah ke atas. Hampir tidak pernah terdengar ada penjual es atau mie ayam yang jadi ODP (orang dalam pengawasan) atau PDP (pasien dalam pengawasan), yang ada direktur, dirjen, menteri.
Apa karena orang kecil lebih kebal akibat “mampu” makan sembarangan dibanding mereka yang makannya pilih-pilih dan bergizi? Atau karena orang kecil ditolak kalau memeriksakan diri, harus lewat puskesmas, harus ada rujukan dan sebagainya? Sementara puskemas sepertinya punya prinsip sesedikit mungkin merujuk pasien ke rumah sakit.
Mungkin perlu ada sistem pengobatan jarak jauh lewat fasilitas telekomunikasi, tidak hanya untuk WFH (work from home) atau distance learning sambil operator menyediakan fasilitasnya di pusat-pusat permukiman, tidak hanya di perumahan mewah. Komunikasi jarak jauh masyarakat dengan dokter, rumah sakit dengan pusat-pusat penanganan Covid-19 dilakukan secara digital, menghemat waktu dan biaya.
Namun, perlu pula kesiapan operator untuk tidak arogan, siap membagi, sharing, digital dengan operator yang belum mampu menjangkau suatu kawasan sementara pelanggannya membutuhkan informasi dan penanganan dokter. Dalam menangani serangan virus korona, orang tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Capai, biaya besar, hasilnya minim.
Semua komponen bangsa perlu bergerak dengan komando yang tegas, jangan meremehkan situasi, sekecil apa pun. Di sini peranan telekomunikasi sangat dominan selain tentu penanganan mediknya yang tidak bisa diungguli apa pun.
Layanan telko bisa dilakukan dari mana saja, remote, tetapi layanan fisik, dokter perawat, harus secara fisik pula. Sayangilah tenaga-tenaga medis yang kini sudah jadi pahlawan-pahlawan yang tidak pernah atau sempat mengeluh. ***