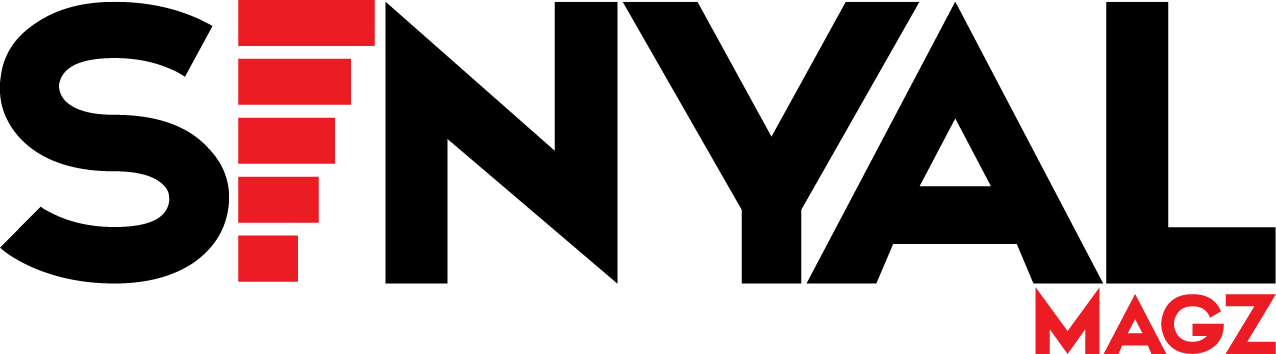sinyal.co.id
RAMBUT sama hitam, isi kepala bisa berbeda dan laju kuda tidak pernah sama kecuali dikendalikan, diikat jadi satu. Itulah sebabnya ada pacuan kuda, karena ada kuda yang bisa berlari cepat, ada pula yang mampu berlari lebih cepat lagi.
Di rezim pemerintahan saat ini amsal (perumpamaan) demikian bisa diterapkan. Walau Kepala Negara sudah menyampaikan arahan, kemampuan penerimaan pembantu-pembantu Presiden dan menerjemahkannya dalam kegiatan kementeriannya bisa berbeda.
Contohnya dalam menekan harga kebutuhan pokok dalam masa Ramadan dan menjelang Idul Fitri kemarin, ketika harga-harga melambung, terutama harga daging sampai Rp120.000 per kilo dari normalnya Rp80.000. Padahal perintah Presiden sudah diberikan Oktober tahun lalu, namun mengantisipasi dengan melakukan kebijakan-kebijakan, kemampuan pembantu Presiden masih sangat kurang.
Tetapi ketika daging sapi ‘digerojok’ ke berbagai pasar tertentu, harga daging sapi tetap bertengger di angka fantastis tadi, dan Jokowi pun geram. Kalau saja menuruti nafsu amarah dan bertepatan dengan iklim isu reshuffle kabinet, tentu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong akan digusur, seperti ketika Rahmat Gobel dilengserkan dengan enteng pada reshuffle seri pertama.
Di periode pemerintah Jokowi Jilid Satu – hingga 2019 ini, istilah siapa cepat dia dapat, tidak berlaku. Apalagi jika itu berkaitan dengan kinerja dua atau lebih kementerian secara bersama-sama, karena kecepatan satu menteri belum tentu bisa diimbangi menteri lain sehingga masyarakat tidak segera dapat menikmati kebijakan menteri yang cepat tadi.
Arogansi sektoral dari para menteri juga masih tumbuh subur, melanjutkan tradisi gerbong-gerbong pemerintahan sebelumnya. Pada masa lalu sudah umum kalau pejabat cenderung menerbitkan kebijakan yang berhasil guna instan, yang sudah berwujud semasa ia masih menjabat, bukan kebijakan yang bisa diterapkan untuk jangka panjang.
Maklum, ada pameo yang tak pernah lekang seperti diungkapkan orang Jawa Barat, “Ngapain mikir jangka pendek atau jangka panjang. Nu penting mah jang ka imah (yang penting (hasil) untuk dibawa ke rumah”.
Sejalan dengan saran UNESCO soal migrasi televisi siaran dari analog ke digital, pemerintah menetapkan batas migrasi paling lambat tahun 2018. Batas itu pun termasuk paling lambat di dunia, karena negara-negara lain menuntaskannya pada tahun 2015, bahkan ada yang switch off (perpindahan) analog ke digital pada tahun 2009.
Walau niat migrasi sudah kencang dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), namun ganjalan muncul dari DPR yang belum juga usai menggarap Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran. Kalaupun RUU itu tahun ini diundangkan, migrasi baru bisa dimulai tahun 2019 atau setelahnya, walau untuk uji coba sudah boleh dilakukan, menggunakan frekuensi milik TVRI yang sudah migrasi sejak tahun lalu.
Tuntasnya migrasi TV analog ke digital sangat ditunggu banyak pihak. Dari sisi masyarakat luas, televisi siaran digital dapat membantu bila terjadi bencana alam, karena informasi tentang bencana alam bisa disiarkan secara real time, saat itu juga.
Dari sisi bisnis dan industri, selain pemilik lama frekuensi, para pemilik televisi siaran yang ingin mengangkangi frekuensi untuk tujuan komersial lain, pihak yang paling berharap tuntasnya migrasi adalah operator telekomunikasi seluler. Migrasi meninggalkan spektrum frekuensi selebar 150 MHz di rentang 700 MHz, spektrum yang dinilai paling bagus bagi operator untuk memberi layanan seluler generasi keempat (4G) LTE (Long Term Evolution).
Namun para operator masih harus gigit jari. Kalaupun spektrum sudah ditinggalkan televisi siaran, belum ada jaminan spektrum itu dilelang sebelum masa jabatan pemerintah usai pada tahun 2019 dan selewat itu belum tentu menterinya Rudiantara.
Di tataran teknologi informasi, makin rendah frekuensi, makin luas jangkauannya sehingga biaya modal yang harus dikucurkan operator lebih murah. Sebagai gambaran, BTS (Base Transceiver Station) di spektrum 800-900 MHz memiliki cakupan sekitar radius 2 kilometer sampai 5 kilometer.
Cakupan 1800 MHz di bawah 1.000 meter walau dalam penerapan di lapangan radiusnya bisa lebih lebar sedikit. Spektrum 2100 MHz yang digunakan untuk 3G dan akan dipakai 4G LTE jika sudah dinyatakan sebagai teknologi netral, cakupannya lebih sempit lagi yang lebih cocok untuk perkotaan padat trafik percakapan dengan memasang mikrosel atau picosel.
Sisa frekuensi 2300 MHz selebar 30 MHz dan 10 MHz di 2100 MHz akan diperebutkan oleh operator seluler. Pemerintah berencana spektrum itu akan dilelang, namun masih diundur-undur waktunya sehingga membuat gemas operator yang sudah kekurangan frekuensi untuk layanannya.
Saat ini memang terjadi seperti ketidakadilan di kalangan industri seluler karena pemilikan spektrum frekuensi yang tidak imbang. Telkomsel, misalnya, memiliki lebar frekuensi sama dengan XL Axiata, 52,5 MHz di rentang 900 MHz, 1800 Mhz, dan 2100 MHz. Padahal pelanggan Telkomsel sudah lebih dari 154 juta sementara XL Axiata di bawah 50 juta.
Semua operator GSM: Telkomsel, Indosat, XL dan Hutchison Tri Indonesia, sangat mau dan sangat mampu membeli frekuensi tambahan di 2100 MHz dan 2300 MHz jika dilelang. Namun pemerintah juga harus mempertimbangkan keunggulan di banyak hal, antara lain luas cakupan layanan yang sudah dilakukan tiap operator di seluruh Indonesia yang berdampak langsung kepada manfaat bagi masyarakat. Juga soal besaran kontribusi kepada negara dalam bentuk dividen dan pajak, selain kepadatan kapasitas per BTS di perkotaan.
Kalau yang dicari besaran penawaran dalam lelang pasti operator milik asing yang berpeluang menang karena mereka akan dibantu pemilik asingnya yang dengan mudah menggelontorkan biaya modal. Beda dengan Telkomsel yang boleh dikata “tidak punya uang” karena semua pendapatan diserahkan kepada induknya yang BUMN.