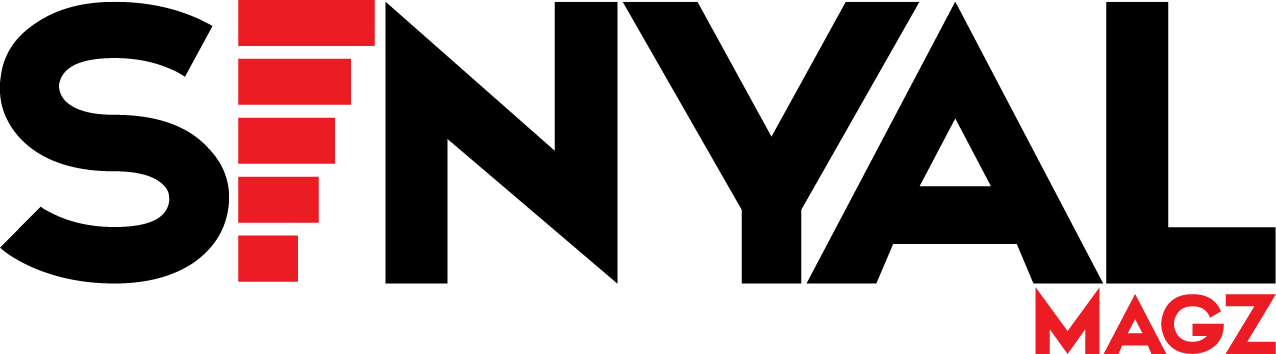sinyal.co.id
PEPATAH Jawa mengatakan, jer basuki mawa beya, yang artinya kurang lebih: untuk mencapai kesejahteraan perlu pengorbanan. Tidak ada hubungannya dengan Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok yang lagi getol menggusur penduduk bantaran sungai di Jakarta, sebagai korban, namun menyejahterakan penduduk lain yang terhindar dari musibah banjir.
Sebenarnya kata “korban” harus ditulis di antara dua tanda kutip, sebab tingkat kehidupan (ke-basuki-an) mereka justru diperbaiki oleh Basuki Ahok, dengan rumah susun yang fasilitasnya komplet. Sementara di bantaran sungai mereka hidup dalam lingkungan yang tidak sehat, berdesak-desakan dan selalu dalam ancaman banjir kiriman.
Namun, kebetulan ada kaitan Ahok sebagai gubernur pertahanan akan mendapat pesaing dua pasang bakal calon gubernur, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylvia Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Kaitannya, pengorbanan warga girli (pinggir kali) menjadi peluru tajam untuk menohok Ahok, dengan alasan tidak manusiawi dan melanggar hukum sebab para warga gusuran itu memiliki hak untuk tinggal di sana.
Dari sisi hukum, hak adalah mutlak, namun hak itu akan menjadi gugur jika kepentingan lebih besar dirugikan. Dalam, kasus Ciliwung, misalnya, pemukiman di bantaran kali membuat aliran air tidak lancar sehingga banjir luber ke mana-mana dan menyengsarakan tidak hanya penghuni bantaran namun juga ratusan ribu warga lainnya di sepanjang sisi Ciliwung.
Apakah para pengritik kebijakan Gubernur DKI itu ikut membahas kenyamanan di rumah susun yang bebas berimpitan, ada lahan bersosialisasi, sekolah gratis untuk anak-anak juga transportasi gratis, dibantu kalau akan berjualan dan sebagainya? Kalau itu masuk dalam agenda serang, pelurunya justru menjadi peluru hampa, hanya bunyinya saja yang keras tetapi tidak mematikan.
Politik memang acapkali menghalalkan cara, namun bukan ini yang jadi masalah. Apakah kemajuan di bidang teknologi telekomunikasi sudah siap dimanfaatkan secara benar oleh masyarakat dengan menjauhi efek-efek negatifnya?
Coba masuk ke satu kawasan kumuh, ketika suatu waktu gang dipenuhi warga yang terpaksa keluar rumahnya karena tak ada ruang cukup untuk – misalnya – baca-tulis, menjahit, atau merangkai bunga. Boro-boro untuk kegiatan itu, yang disebut ruang depan atau ruang tamu sudah jadi ruang tidur karena isi rumah yang berlebihan, rumah petak ukuran 3X5 meter dihuni lebih dari tujuh orang: suami-istri, tiga anak, dan kakek-nenek atau keponakan.
Tidur pun terpaksa berhimpitan dan lahan sedikit di gang menjadi tempat mencari udara segar. Di sini muncul segala kegiatan yang lebih ke arah vokal, ghibah, membicarakan keburukan, kelakuan, kelucuan, atau bahkan memaki orang lain.
Apa hubungannya dengan telko? Kita lihat media sosial, Twitter, Facebook, Instagram dan sebagainya, yang kalau kita buka akan miris membacanya. Tidak sedikit apa yang dilakukan di gang, dimuntahkan di medsos.
Memaki seseorang, melampiaskan kemarahan, dan mengeluarkan semua isi kebon binatang sudah jadi biasa di medsos. Banyak pemakai ponsel pintar memindahkan suasana gang ke medsos dengan mengungkapkan segala macam sampah tanpa tedeng aling-aling.
Jika kita mengomentari seseorang di gang, yang mendengar paling lima-enam orang. Namun di medsos, begitu umpatan diunggah, yang membaca bisa ratusan ribu orang.
Orang harus belajar bahwa efek medsos dan efek gang sangat beda, sehingga orang harus lebih hati-hati dalam memanfaatkan teknologi telekomunikasi itu. Fitnah, hate speech – pengucapan kebencian – kini seolah menjadi jamak dan akan sangat berbahaya jika tidak dilakukan penegakan hukum berdasarkan UU ITE.
Orang yang biasa memfitnah, atau biasa membicarakan kebohongan di warung kopi dengan “audience” terbatas, sulit sadar akan efek luas fitnah yang dilancarkan lewat medsos. Contoh, ketika seseorang menghembuskan isu bahwa seorang menteri bertemu dengan salah seorang ketua partai untuk menyampaikan pesan presiden merestui satu mantan menteri di jajaran kabinetnya untuk jadi bakal calon gubernur.
Pihak Istana kerepotan membantah, tetapi tidak ada tindakan hukum agar si pemitnah yang konon bukan cuma sekali melakukan hal demikian, jera. Fitnah juga diluncurkan orang yang sama dengan sasaran operator telko terbesar, yang dikatakan menjual aset BUMN sehingga sangat merugikan negara.
Juga tentang kasus Indosat Mega Media (IM2), yang bolak-balik dihembuskan orang lewat medsos dan online. Kasus IM2 menjadi sangat berat, karena penegak hukum lebih memperhatikan fitnah dan tidak mendengar pertimbangan-pertimbangan hukum di telekomunikasi, apalagi didukung pendapat BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) bahwa ada kerugian negara sampai Rp1,3 triliun. Di negara kita, BPK merupakan super body yang pendapatnya tidak bisa dibantah, seperti dalam kasus Sumber Waras.
Menarik juga pengulangan berita bahwa SBY pernah menikah dan punya dua anak sebelum masuk Akabri dan menikah dengan Ani. Walau SBY pernah melaporkan sumber berita yang sama ke Polri tetapi lalu dilakukan penyelesaian, namun berita yang kedua lebih lengkap dengan nama-nama dan waktu kejadian yang mendukungnya, dan belum ada upaya melaporkannya ke polisi.
Mengerikan sekali membayangkan apa yang akan terjadi lima atau 10 tahun ke depan, ketika orang merasa bahwa medsos merupakan forum bebas sebebas bebasnya untuk menyampaikan pendapat. Apalagi jika seseorang meluncurkan fitnah atau hoax dan mendapat reaksi keras masyarakat, ia cukup menghilangkan diri tanpa harus membela apa yang sudah diucapkannya, apalagi jika fitnah itu dikemas dalam karya seni, misalnya puisi.
Pilkada Gubernur DKI awal tahun depan juga berpotensi besar terjadinya penyebaran fitnah. Polri memang sudah siap akan menindak orang yang meluncurkan ucapan kebencian yang muncul di medsos, tetapi itu belum cukup, harus ada hukuman berat bagi yang bersalah.
Moch. S. Hendrowijono